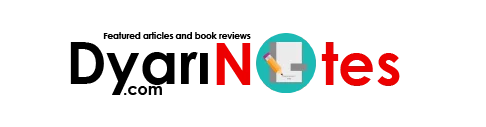Ada satu prolog kocak di tengah “Kecerdasan Emosional 0-80” yang ingin kami bawa kepermukaan, hari ini. Jadi ketika lagi asyik scroll media sosial, lalu ada satu komentar yang isinya… “Wah😀, berasa kuliah dua semester dalam satu thread?” Atau, saat lagi kumpul santai, tiba-tiba ada teman yang berlagak jadi Google Assistant berjalan: “semua ditanya, semua dijawab, bahkan yang enggak ditanya pun di-spill habis-habisan”.
Momen itu sering membuat kita diam-diam bergumam, “Ya ampun, santai banget sih, gak semua hal perlu direspons kalee!” Gak capek apa?
Fenomena ini bukan cuma soal latah atau keasyikan bersuara, ini tentang volume noise di kepala dan hati yang sepertinya sedang mentok di angka 80, sementara volume control alias Kecerdasan Emosional (EQ) masih di angka 0.
Hero to Zero.
Kita ini looh, hidup di era “Serba Tahu, Serba Jawab”, seolah ada invisible notes yang akan meledak kalau kita gagal menimpali setiap prompt di kehidupan. Padahal, ada kalanya ‘diam’ itu jauh lebih mahal daripada ocehan yang tumpah ruah.
Lanjut?
Kebodohan: Semakin Banyak Ia, Semakin Terlihat
Kecerdasan Emosional 0-80.
Kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita begitu terobsesi untuk selalu tampil on? Mungkin ini efek dari budaya FOMO “takut ketinggalan” yang sudah bermetamorfosis menjadi FOAR (Fear of Always Responding), “takut dibilang: lue ternyata gak sensi banget yaa”.
Semakin banyak yang kita tutupi dengan kata-kata, semakin besar kemungkinan “kebodohan” yang sesungguhnya justru terlihat. Kebodohan di sini bukan berarti IQ rendah, ya, tapi merujuk pada ketidakmampuan untuk memilah: Kapan harus diam, kapan harus bicara, dan seberapa banyak.
Maka, hadirlah sebuah hikmah kuno yang tajam, yang konon dinisbatkan kepada ulama besar seperti Ibnu ‘Athaillah. Kutipan itu bilang-nya gini: “kebodohan seseorang adalah ketika ia selalu menjawab setiap pertanyaan, menceritakan semua yang dilihat, dan menyebut semua yang diketahui.”
Coba cari jedah, kita resapi.
Secara modern, ini adalah definisi paripurna dari “Kurang Filter Emosional”. Kita gak banget perlu jadi ensiklopedia berjalan untuk diakui, malah kadang, upaya kita untuk menjelaskan segalanya justru menjadi bumerang yang mengungkapkan ketidakmatangan jiwa.
Kami kutip inti dari hikmah ini, sebagai berikut:
مَنْ رَأَيْتَهُ مُجِيْبًا عَنْ كُلِّ مَا سُئِلَ، وَمُعَبِّرًا عَنْ كُلِّ مَا شَهِدَ، وَذَاكِرًا كُلَّ مَا عَلِمَ، فَاسْتَدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى وُجُوْدِ جَهْلِهِ
“Barang siapa yang engkau lihat selalu menjawab setiap apa yang ditanyakan kepadanya, mengungkapkan setiap apa yang disaksikannya, dan menyebutkan setiap apa yang diketahuinya, maka ambillah itu sebagai tanda adanya kebodohan padanya.”
Sumber:
- Kitab: Al-Hikam (Judul asli: الحكم العطائية والمناجاة الإلهية)
- Pengarang: Syekh Ibnu ‘Atha’illah As-Sakandari (Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu ‘Atha’illah As-Sakandari)
- Tahun: Akhir abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Ibnu ‘Atha’illah wafat pada tahun 709 Hijriah (sekitar tahun 1309 Masehi).
FunFact-nya: Ini bukan soal melarang kamu beropini, lhoo.
Tapi, ini adalah undangan untuk merenungkan: apakah dorongan untuk selalu merespons itu datang dari kebutuhan untuk berbagi atau kebutuhan untuk divalidasi? Garis tipis inilah yang akan membawa kita pada jebakan fatal: over-explaining dan godaan know-it-all.
Lalu, bagaimana?
Cara Menemukan Garis Jebakan Over-Explaining dan Godaan Know-It-All
Oke, kita sudah tahu inti masalahnya.
Kita seringkali keasyikan menekan tombol reply dan publish tanpa jeda. Lalu, bagaimana cara menemukan garis batas “cukup” yang seringkali tersembunyi itu? Nah, kami acak beberapa cara kocak tapi serius untuk menemukan filter pribadi kamu, menjauh dari zona toxic over-explaining.
Tanpa berisik, kami sebut itu dengan:
1. Teori Silence is Gold (dan juga Receh): Tahan Jempol 3 Detik
Sebelum kamu mengetik balasan panjang atau memotong pembicaraan, hitung 1-2-3 di dalam hati. Kalau setelah 3 detik jawaban itu masih terasa urgent dan relevan, silakan. Kalau tidak? Selamat, kamu baru saja menyelamatkan diri dari clown moment.
Istilah populernya: “Delay Gratification”: menunda kesenangan untuk selalu tampil paling tahu, demi kualitas interaksi yang lebih baik.
2. Jebakan The Unsolicited Advice: Prinsip Ask, Don’t Assume
Kamu punya insight keren? Bagus.
Tapi, jangan pernah memberikan saran, cerita, atau jawaban kalau gak ditanya. Kalau kamu merasa terpanggil untuk ‘membantu’, tanyakan dulu, “Mau dengar pendapatku?” Kalau responsnya datar, anggap saja kamu baru saja melewati checkpoint emosional.
Ini adalah skill “Respecting Boundaries” versi santai.
3. Deteksi The Double Response: Is it Necessary, or Just Extra?
Setelah kamu selesai bicara, coba refleksi. Apakah ada kata-kata yang bisa kamu hapus tanpa mengubah maknanya? Kalau ada, itu artinya kamu sudah kena virus over-explaining: memberi informasi yang berlebihan, yang ujung-ujungnya membuat orang lain lelah atau, lebih parahnya, ilfeel.
Ingat, dalam komunikasi, “Less is More” bukan cuma ‘cakeeep’ buat desain, tapi juga buat lisan.
4. Hentikan Show-Off Sinyal: Jadikan Dirimu The Student, Bukan The Lecturer
Godaan know-it-all sering muncul saat kita ingin menghubungkan setiap cerita orang lain dengan pengalaman kita. “Oh, kamu ke Bali? Aku udah pernah 10 kali, dan tahu gak… bla,bla,bla” Stop! Anggap saja kamu itu adalah murid abadi.
Fokus mendengarkan 80%, bicara 20%. Daripada berusaha validasi diri sebagai yang terpintar, lebih baik kamu validasi orang lain dengan mendengarkan cerita mereka. Ini namanya “Active Listening”, sebuah soft skill yang langka.
5. Filter The Gossip Gate: Tanya: Is it Kind, Is it True, Is it Needed?
Ini sebenarnya filter klasik yang sangat ampuh, terutama saat kita gatal ingin menceritakan “semua yang dilihat.”
Sebelum lisan bergerak, saring dulu infomu dengan tiga pertanyaan ini:
- Apakah ini baik (kind)?
- Apakah ini benar (true)?
- Apakah ini perlu (needed)?
Kalau salah satu jawabannya “tidak,” maka simpan saja. Kita perlu menjaga “Personal Brand Integrity” dengan tidak menyebarkan noise yang tidak penting.
Ketika Menjawab, Menceritakan, dan Menyebut Menjadi Makin Buruk
Kecerdasan Emosional 0-80.
Minggu lalu, kita menyaksikan sendiri sebuah adegan secara live show tentu saja, di kedai kopi. Bukan MMA atau tinju jalanan. Jadi, ada dua orang sedang berdiskusi, katakanlah tentang proyek startup.
Yang satu, si Abil, dengan antusias menceritakan problem yang sedang ia hadapi. Baru sampai di kalimat “jadi-nya….”, si Bubu langsung menyambar, “Oh, gampang! Itu namanya Product-Market Fit yang belum ketemu. Kamu harusnya sudah baca buku: ‘Si Titit kembar’, dia bilang begini. Terus, jangan lupa framework XYZ. Intinya, kamu sudah salah dari awal.”
Si Bubu bicara tanpa jeda selama lima, tujuh, sepuluh menit penuh.
Wajah si Abil, yang awalnya antusias, perlahan berubah menjadi datar, merah, kemudian tertutup rasa segan dan agak kesal.
Si Bubu tidak sadar, upaya dia untuk menjawab semua (padahal si Abil belum selesai bertanya), menceritakan semua (mengenai buku dan framework yang ia tahu), dan menyebut semua (istilah-istilah keren) justru membuat si Abil merasa kecil dan tidak didengarkan.
Alhasil pun komunikasi terputus, bukan karena si Bubu bodoh, tapi karena ia gagal menunjukkan empati dalam volume 80. Itulah contoh nyata betapa buruknya niat baik yang dieksekusi dengan zero filter EQ.
Okey, si Bubu mungkin pintar, tapi ia menciptakan jurang yang lebar antara dirinya dan si Abil. Tujuannya enggak nyampe, malah merusak hubungan. Inilah yang terjadi ketika kita mengizinkan ego untuk berteriak lebih kencang daripada kebijaksanaan.
Yang Awalnya Abil mau traktik kopi, kelanjutan-nya “gak jadi deh…”
Yaa, begitulah😒…
Ketidakmampuan Menahan Lisan = Tanda Ketidakmatangan Jiwa?
Apa yang kita ucapkan dan kita tahan adalah cerminan paling jujur dari kedalaman batin kita. Dorongan untuk selalu mengisi ruang kosong dengan suara, selalu membalas setiap challenge dengan defense, dan selalu melabeli setiap fakta dengan pengetahuan kita, adalah alarm keras bahwa jiwa kita masih dalam proses pertumbuhan. Alias, belum matang.
Kedewasaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak term keren yang kamu kuasai, tapi dari seberapa mahir kamu mengelola emosi dan lisan.
Kecerdasan Emosional adalah filter super canggih yang memisahkan antara noise dan value. Mari kita kurangi volume 80 dari ego kita dan mulai belajar menikmati ketenangan di antara angka 0-80 tersebut.
Karena, seringkali, keberanian terbesar adalah keberanian untuk diam.
Ketahui-nya: Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui kapan harus bicara dan kapan harus menahan diri. Sebab: keheningan yang tepat waktu, jauh lebih berharga daripada seribu kata yang sia-sia.
Salam Dyarinotescom.